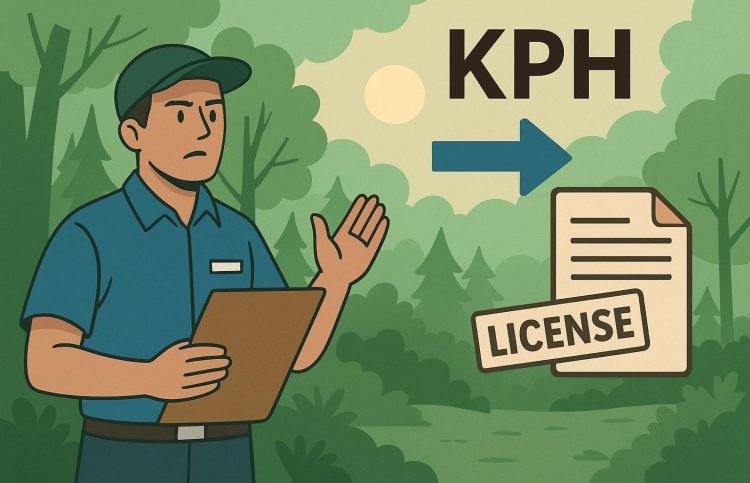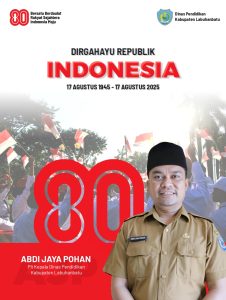Korannusantara.id – Opini, Bayangkan sebuah lembaga yang dibentuk dengan harapan besar: menjaga hutan dari degradasi, mempertemukan kepentingan negara dan masyarakat, serta menghadirkan keadilan ekologis di tingkat tapak.
Lembaga itu bernama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), gagasan yang lahir dari semangat reformasi kehutanan awal 2000-an, ketika negara berusaha memperbaiki kerusakan hutan yang ditinggalkan oleh sistem konsesi sentralistik era Orde Baru.
Ketika pertama kali diperkenalkan melalui UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, KPH diposisikan sebagai aktor utama dalam desentralisasi pengelolaan hutan. Ia diharapkan menjadi ujung tombak negara di tingkat tapak: lembaga teknokratis yang memahami kondisi ekologi dan sosial masyarakat di sekitar hutan, tetapi juga cukup otonom untuk mengambil keputusan strategis tanpa harus menunggu instruksi dari Jakarta. Dalam bayangan idealnya, KPH bukan sekadar unit kerja, melainkan institusi pengelolaan wilayah hutan yang hidup, adaptif, dan berakar dilokalitasnya.
Namun, dua dekade setelah gagasan itu bergulir, realitas di lapangan menunjukkan cerita yang berbeda. KPH memang tumbuh di seluruh Indonesia, secara administratif ada ratusan unit yang telah terbentuk tetapi sebagian besar justru beroperasi dalam ketidakpastian: anggaran yang minim, kewenangan terbatas, dan struktur organisasi yang lebih mirip perpanjangan birokrasi ketimbang institusi pengelola. Di tengah upaya mereka menegakkan prinsip pengelolaan tapak, hadir Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020) yang mengubah peta besar tata kelola kehutanan Indonesia.
Melalui kebijakan turunan seperti PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan sejumlah Peraturan Menteri LHK tahun 2021, fungsi KPH mengalami transformasi yang signifikan. Jika sebelumnya KPH memiliki ruang untuk mengelola, merencanakan, dan melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan secara langsung, maka kini perannya banyak bergeser menjadi fasilitator perizinan, menghubungkan antara pemegang izin usaha, masyarakat, dan pemerintah pusat. Dalam logika baru yang dibangun oleh UUCK, pengelolaan hutan tidak lagi berpusat pada institusi publik di daerah, tetapi pada sistem perizinan yang dikontrol pusat.
Akibatnya, KPH yang dulu digadang sebagai wujud nyata devolusi pengelolaan hutan berubah menjadi aktor administratif dalam sistem perizinan investasi. Istilah “pengelola hutan” perlahan bergeser menjadi “penghubung izin.” Dan di titik inilah muncul pertanyaan mendasar: Apakah transformasi ini sekadar penyesuaian kelembagaan, atau justru menandai kemunduran ideologi desentralisasi kehutanan yang dahulu menjadi landasan lahirnya KPH?
Dari Pengelolaan ke Administrasi
Sebelum UUCK hadir, KPH memiliki posisi strategis dalam desain desentralisasi kehutanan. Berdasarkan PP No. 6 Tahun 2007 jo. PP No. 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, KPH bertugas menyusun Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), mengelola data potensi sumber daya hutan, serta memfasilitasi kegiatan perhutanan sosial, rehabilitasi, dan perlindungan hutan.
Dengan kata lain, KPH bukan hanya pelaksana teknis, melainkan otoritas pengelolaan di tingkat tapak, tempat kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan nyata.
Namun setelah UUCK diberlakukan pada tahun 2020 dan diturunkan dalam PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, fungsi itu berubah drastis. Kewenangan yang dahulu melekat pada KPH kini dipusatkan di tangan Menteri Kehutanan. Seluruh bentuk kegiatan pemanfaatan kawasan hutan baik untuk usaha kayu, jasa lingkungan, wisata alam, maupun hutan tanaman harus melalui sistem perizinan terintegrasi di pusat yang disebut Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Akibatnya, KPH tidak lagi menjadi pengambil keputusan dalam pengelolaan hutan di wilayahnya. Ia kini lebih banyak berperan sebagai penghubung administrasi antara pemohon izin, pelaku usaha, dan pemerintah pusat.
Dalam banyak kasus, KPH di lapangan hanya menerima surat tembusan izin yang sudah diterbitkan dari Jakarta, tanpa ruang untuk menilai kelayakan sosial-ekologis kegiatan tersebut.
Padahal, mereka yang paling memahami kondisi tapak: topografi, kerapatan vegetasi, hingga relasi sosial masyarakat sekitar hutan. Kewenangan yang dulu berbasis pada local knowledge kini digantikan oleh logika regulatory simplification, di mana kecepatan perizinan menjadi ukuran utama keberhasilan birokrasi.
Perubahan ini tidak sekadar teknokratis. Ia menunjukkan pergeseran paradigma yang lebih dalam: Dari pengelolaan berbasis wilayah (management by area) menuju pengendalian berbasis izin (management by license). Di atas kertas, sistem ini dianggap efisien dan mendukung investasi hijau. Tetapi di lapangan, ia sering menciptakan kekosongan otoritas di tingkat tapak karena yang memiliki izin tidak selalu hadir secara fisik, sementara KPH yang ada di lapangan tidak punya kuasa untuk menegur atau mengatur.
Kita bisa melihat paradoks ini dalam praktik perhutanan sosial. KPH sebelumnya berperan penting sebagai fasilitator pembentukan kelompok, pendamping penyusunan rencana kerja, sekaligus pengendali kegiatan di lapangan. Pasca-UUCK, sebagian fungsi itu berpindah ke unit pelaksana teknis pusat, sementara KPH hanya berperan memverifikasi dan melaporkan kegiatan.
Kondisi ini menandakan pergeseran dari institusi pengelola menjadi institusi administratif. KPH kini lebih sibuk dengan pelaporan dan validasi sistem informasi kehutanan (SIKAWAN, SIMONTANA, dsb.) ketimbang pengelolaan lapangan.
Fungsi strategis seperti pengendalian kebakaran, pengawasan izin, atau mediasi konflik sering tertinggal karena minimnya kewenangan dan dukungan anggaran. Ironisnya, meskipun UUCK membawa semangat deregulasi, bagi KPH justru yang terjadi adalah devolusi semu: otonomi yang dijanjikan tak pernah benar-benar tiba. Mereka tetap berada di garis depan, tetapi tanpa senjata kebijakan untuk bertindak.
Apabila arah ini terus berlanjut, maka keberadaan KPH akan semakin sulit dibedakan dari struktur birokrasi kehutanan biasa, padahal ia didesain sebagai lembaga pengelolaan adaptif yang mampu menjembatani antara kepentingan ekologi, sosial, dan ekonomi di tingkat tapak.
Dari sinilah muncul pertanyaan yang semakin relevan: Apakah kita masih berbicara tentang pengelolaan hutan, atau hanya tentang pengadministrasian izin?
Dilema Otonomi Kelembagaan
Perubahan kebijakan pasca-UUCK bukan hanya persoalan teknis perizinan, tetapi juga krisis identitas kelembagaan. Sejak awal pembentukannya, KPH dirancang untuk memiliki otonomi fungsional yakni keleluasaan dalam mengambil keputusan pengelolaan hutan sesuai kondisi sosial-ekologis wilayahnya.
Dalam berbagai dokumen perencanaan, KPH disebut sebagai “unit pengelolaan terkecil” yang mampu mengintegrasikan fungsi produksi, lindung, dan sosial dalam satu lanskap. Namun dalam praktiknya, otonomi itu tidak pernah tumbuh sepenuhnya; ia selalu tergantung pada struktur birokrasi di atasnya.
Pasca-UUCK, ketergantungan ini semakin dalam. KPH memang diberi tanggung jawab besar dari menyusun rencana pengelolaan hingga memastikan kepatuhan izin di lapangan tetapi tanpa kewenangan, sumber daya, dan legitimasi politik yang memadai. Mereka harus bertanggung jawab atas hasil pengelolaan hutan, padahal keputusan penting seperti siapa yang boleh mengakses, menanam, atau memanfaatkan hasil hutan kini ditentukan oleh pusat. Inilah dilema klasik yang dihadapi KPH: dituntut mandiri, tapi tidak diberi ruang untuk benar-benar berdaulat.
Posisi KPH seperti “manajer tanpa kunci gudang.” Mereka bertugas menjaga aset yang mereka tidak bisa kelola sepenuhnya. Misalnya, ketika perusahaan pemegang PBPH menunggak kewajiban rehabilitasi atau melanggar batas wilayah kerja, KPH tidak memiliki dasar hukum untuk memberikan sanksi. Mereka hanya bisa melaporkan ke pusat melalui sistem online atau surat resmi, yang penyelesaiannya bisa memakan waktu berbulan-bulan.
Dalam konteks perhutanan sosial pun demikian: Kelompok Tani Hutan (KTH) seringkali menggantungkan pendampingan teknis ke KPH, tapi KPH sendiri kekurangan anggaran operasional dan kewenangan untuk menindaklanjuti.
Secara kelembagaan, KPH terjepit antara dua logika yang saling bertentangan
Di satu sisi, logika administratif menempatkan mereka sebagai perpanjangan tangan birokrasi pusat, harus patuh, terukur, dan berorientasi pada laporan. Di sisi lain, logika pengelolaan menuntut mereka untuk adaptif, cepat merespon perubahan, dan berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal. Kontradiksi ini membuat banyak KPH kehilangan daya inisiatif, karena setiap langkah harus menunggu arahan vertikal.
Contoh yang sering muncul adalah pada KPH yang sudah berusaha membangun model bisnis kehutanan sosial, seperti pengembangan madu hutan, kopi agroforestri, atau jasa wisata alam.
Program-program itu sering berhenti di tengah jalan karena tidak ada mekanisme legal untuk mengelola pendapatan secara langsung. Semua Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) harus disetor ke kas negara, sementara KPH tidak memiliki instrumen penganggaran untuk memanfaatkannya kembali di lapangan. Kemandirian ekonomi yang diharapkan dari KPH akhirnya menjadi ilusi administratif.
Di sisi lain, terdapat paradoks tanggung jawab. Ketika terjadi kebakaran hutan, penebangan liar, atau konflik tenurial, publik dan pemerintah daerah sering menuntut KPH bertanggung jawab. Tetapi dalam hal pengambilan keputusan strategis misalnya penetapan izin, perubahan fungsi kawasan, atau alokasi investasi, KPH sama sekali tidak dilibatkan. Ini menjadikan posisi KPH sangat rentan: disalahkan ketika gagal, tapi diabaikan ketika menentukan arah kebijakan.
Dari perspektif kelembagaan, situasi ini dapat disebut sebagai “institusi tanpa arena” (arena-less institution). KPH memiliki struktur, personel, dan wilayah kerja, namun tidak memiliki arena keputusan di mana mereka bisa memengaruhi kebijakan secara signifikan.
Mereka adalah pemain yang hadir di lapangan, tapi bukan pembuat aturan permainan.
Krisis otonomi kelembagaan KPH ini tidak hanya berdampak pada efektivitas pengelolaan hutan, tetapi juga pada semangat para rimbawan di lapangan. Banyak yang mulai mempertanyakan relevansi peran mereka, apakah mereka masih “pengelola” hutan, atau sekadar pelapor kegiatan pihak lain. KPH yang dulunya diimpikan sebagai lembaga pembelajaran kebijakan (learning organization) kini lebih menyerupai lembaga administratif yang mengukur keberhasilan dari jumlah laporan yang dikirim, bukan dari perubahan sosial-ekologis yang dihasilkan.
Jika keadaan ini tidak diperbaiki, KPH akan terus terjebak dalam siklus ketergantungan struktural yang dilahirkan dengan semangat desentralisasi, tapi tumbuh dalam sistem yang menolak desentralisasi itu sendiri.
Maka, persoalannya bukan sekadar bagaimana memperkuat kapasitas teknis KPH, tetapi bagaimana mengembalikan legitimasi kelembagaannya: memberi ruang bagi KPH untuk mengambil keputusan, mengelola sumber daya, dan membangun kemitraan di tingkat tapak tanpa harus terus-menerus menunggu perintah dari pusat.
Menuju Reposisi KPH: Dari Pengelola Tapak ke Mediator?
Pergeseran fungsi KPH dalam rezim pasca-UUCK tidak harus dibaca semata sebagai kemunduran, tetapi bisa juga menjadi momentum untuk menata ulang peran kelembagaan. Jika konsep “pengelolaan” dalam arti klasik kini tereduksi oleh sistem perizinan dan birokrasi pusat, maka KPH perlu menemukan ruang peran baru yang lebih relevan dengan konteks politik dan ekonomi kehutanan hari ini: bukan lagi sekadar “penjaga hutan”, tetapi mediator kebijakan di tingkat tapak.
Sebagai mediator, KPH dapat memainkan fungsi strategis yang selama ini terabaikan: menjembatani kepentingan negara, dunia usaha, dan masyarakat lokal.
Dalam sistem yang semakin kompleks, di mana izin usaha, program perhutanan sosial, dan inisiatif restorasi berjalan berdampingan, KPH bisa menjadi arena negosiasi kebijakan, tempat di mana kepentingan ekologis dan ekonomi dipertemukan, bukan dipertentangkan.
Fungsi mediasi ini sebenarnya selaras dengan roh awal pembentukan KPH: menghadirkan tata kelola hutan yang berbasis wilayah (territorial governance), bukan semata berbasis izin.
Untuk memainkan peran itu, KPH perlu direposisikan tidak hanya sebagai pelaksana teknis Kementerian, tetapi sebagai aktor kebijakan daerah yang memiliki kapasitas deliberatif.
Artinya, mereka harus diberi ruang untuk memfasilitasi dialog kebijakan di tingkat tapak baik antara pemegang izin PBPH, kelompok perhutanan sosial, maupun pemerintah daerah.
Dengan begitu, KPH bisa menjadi broker kelembagaan yang memastikan setiap bentuk pemanfaatan hutan tetap berada dalam koridor keberlanjutan ekologi dan keadilan sosial.
Namun reposisi ini hanya mungkin jika ada rekonstruksi legitimasi kelembagaan.
Pertama, KPH perlu diakui bukan sekadar sebagai unit pelaksana, melainkan sebagai otoritas wilayah pengelolaan. Artinya, setiap kebijakan yang berdampak pada wilayah kerja KPH baik perizinan, restorasi, maupun program pembangunan harus melalui proses konsultasi atau verifikasi di KPH. Hal ini dapat dilakukan tanpa harus mencabut kewenangan pusat, tetapi dengan memperkuat mekanisme koordinasi berbasis wilayah.
Kedua, diperlukan reformasi pembiayaan kelembagaan. Selama ini, KPH bergantung pada APBN atau APBD yang jumlahnya terbatas dan sifatnya tahunan. Untuk menjadi mediator yang efektif, KPH harus memiliki sumber daya yang lebih fleksibel, misalnya melalui trust fund atau mekanisme bagi hasil dari PNBP kehutanan yang dikembalikan ke wilayah pengelolaan. Dengan skema semacam itu, KPH dapat mendanai kegiatan strategis seperti pendampingan masyarakat, pengawasan izin, dan inisiatif ekonomi hijau tanpa harus menunggu proyek pusat turun.
Ketiga, KPH perlu mengembangkan kapasitas adaptif: kemampuan untuk bernegosiasi, memediasi konflik, dan membangun jejaring lintas sektor. Peran baru sebagai mediator tidak hanya membutuhkan keterampilan teknis kehutanan, tetapi juga soft skills dalam komunikasi sosial, analisis kebijakan, dan manajemen kolaboratif.
KPH yang efektif di masa depan bukanlah yang paling banyak menanam pohon, tetapi yang paling mampu mempersatukan kepentingan berbagai aktor dalam menjaga kelestarian kawasan hutan.
Contoh potensial dari peran ini sebenarnya sudah mulai terlihat di beberapa lokasi
KPH menjadi penghubung antara kelompok tani hutan dengan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) serta mitra swasta yang berinvestasi dalam agroforestri. Selain itu, peran KPH sebagai fasilitator juga dilakukan kolaborasi antara masyarakat adat, perusahaan, dan LSM dalam program restorasi gambut menunjukkan bahwa fungsi mediasi bisa menjadi kekuatan baru KPH bahkan tanpa kewenangan izin sekalipun.
Dengan demikian, masa depan KPH tidak harus dilihat dalam kerangka kehilangan kekuasaan, tetapi pergeseran jenis kekuasaan: dari kekuasaan administratif ke kekuasaan relasional.
Dalam konteks tata kelola sumber daya alam modern, kekuasaan semacam ini justru lebih relevan karena kekuatan terbesar kini bukan terletak pada siapa yang mengeluarkan izin, tetapi pada siapa yang mampu membangun kesepakatan dan memastikan komitmen di lapangan.
Penutup: Mengembalikan Jiwa Pengelolaan Tapak
KPH lahir dari semangat besar: mengembalikan pengelolaan hutan ke tangan mereka yang paling memahami hutan para rimbawan di tapak dan masyarakat yang hidup di sekitarnya.
Ia dirancang sebagai wujud devolusi pengelolaan hutan, bukan sekadar desentralisasi administratif. Karena di balik gagasan teknokratis tentang “unit pengelolaan”, tersimpan nilai politik yang jauh lebih mendalam: kemandirian lokal, pengetahuan tapak, dan legitimasi sosial sebagai dasar kelestarian.
Namun dalam perjalanan sejarahnya, terutama setelah hadirnya rezim UUCK, jiwa itu perlahan memudar. Pengelolaan hutan kini lebih banyak diatur oleh mekanisme izin, bukan oleh logika ekologi atau sosial. Hubungan antara negara dan masyarakat hutan kembali dipisahkan oleh prosedur birokrasi, dan KPH, yang seharusnya menjadi jembatan di antara keduanya terjebak dalam kerangkeng administratif.
Kita sedang menyaksikan apa yang bisa disebut sebagai “depolitisasi pengelolaan tapak”: ketika pengelolaan hutan direduksi menjadi urusan laporan dan izin, bukan lagi ruang perjuangan untuk keberlanjutan dan keadilan. Padahal, tanpa pengelolaan tapak yang hidup, seluruh rancangan kebijakan besar di tingkat nasional kehilangan maknanya.
Keberhasilan program perhutanan sosial, rehabilitasi, atau investasi hijau tidak akan pernah tercapai jika di lapangan tidak ada institusi yang memahami lanskap sosial-ekologis secara utuh. Dalam konteks inilah, mengembalikan jiwa pengelolaan tapak bukanlah langkah romantik ke masa lalu, tetapi strategi rasional untuk memastikan efektivitas kebijakan kehutanan di masa depan.
Mengembalikan jiwa itu berarti menghidupkan kembali nilai-nilai yang dulu melandasi pembentukan KPH: kedekatan dengan masyarakat, adaptasi terhadap ekologi lokal, dan keberanian mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan lapangan.
KPH tidak boleh hanya menjadi perpanjangan tangan izin; ia harus menjadi penafsir kebijakan di tingkat tapak, memastikan bahwa kebijakan nasional benar-benar bermakna bagi masyarakat dan ekosistem yang diatur.
Untuk menuju ke sana, pemerintah perlu melakukan langkah konkret:
• Pertama, menegaskan kembali posisi KPH sebagai otoritas pengelolaan wilayah, bukan sekadar pelaksana teknis.
• Kedua, membuka ruang otonomi dan inovasi di tingkat tapak dengan mekanisme penganggaran yang lebih fleksibel.
• Ketiga, menumbuhkan kembali etos rimbawan sebagai pamong hutan, bukan pegawai hutan yakni mereka yang memimpin dengan pengetahuan, bukan sekadar menjalankan perintah.
Karena pada akhirnya, keberlanjutan hutan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa banyak izin yang dikeluarkan, tetapi oleh seberapa dalam pengelolaan itu memahami kehidupan di bawah kanopi hutan. Jika negara ingin menjadikan hutan sebagai pilar pembangunan hijau, maka ia harus berani mempercayakan kembali pengelolaannya kepada mereka yang berdiri paling dekat dengannya, KPH di tingkat tapak.
Di sanalah masa depan hutan Indonesia sesungguhnya ditentukan: bukan di meja birokrasi, tetapi di tanah yang basah oleh kerja dan pengetahuan para rimbawan.