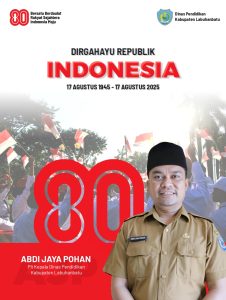Pendahuluan: Suara yang Hilang di Tengah Kebisingan
Setiap dokumen kebijakan kehutanan, pidato pejabat atau laporan proyek konservasi, nama masyarakat hutan hampir selalu hadir seolah mereka adalah pusat dari segala upaya penyelamatan hutan. Masyarakat digambarkan sebagai penjaga terakhir ekosistem, mitra strategis pembangunan, bahkan simbol moral dari keberlanjutan. Namun, ironinya, semakin sering nama mereka disebut, semakin redup pula suara mereka terdengar.
Di tengah gempita jargon “partisipasi”, “pemberdayaan”, “perhutanan sosial”, dan lainnya, kita dihadapkan pada sebuah kebisingan wacana, ruang publik yang tampak ramai dengan klaim keberpihakan, tetapi sesungguhnya hening dari suara yang paling hakiki. Dalam kebisingan itu, yang terdengar paling keras justru suara negara, lembaga donor, atau lembaga swadaya masyarakat yang berbicara atas nama mereka.
Kita sedang menyaksikan paradoks yang halus tapi berbahaya, ketika negara dan lembaga-lembaga pembangunan sibuk “memberdayakan masyarakat,” sesungguhnya mereka sedang memproduksi representasi tentang masyarakat itu sendiri. Masyarakat hutan dijinakkan menjadi citra ideal bahwa warga yang patuh pada prosedur, kooperatif dengan pendamping, dan sesuai dengan indikator proyek. Tetapi dalam ruang pengambilan keputusan yang menentukan nasib hutan mereka, suara mereka sering kali tidak diundang, atau hadir hanya sebagai formalitas.
Kita bisa melihat fenomena ini dalam banyak inisiatif seperti perhutanan sosial yang sarat administrasi, proyek karbon yang berbasis persetujuan dokumen tanpa pemahaman mendalam, hingga kampanye restorasi yang menampilkan wajah masyarakat dalam spanduk, tapi tidak melibatkan mereka dalam desain kebijakan. Semua itu melahirkan kondisi di mana suara masyarakat hadir sebagai gema, bukan sebagai sumber bunyi.
Maka, ketika kita bertanya “siapa yang berdaulat atas hutan,” sesungguhnya kita juga harus bertanya “siapa yang berhak berbicara tentang hutan.” Sebab kekuasaan bukan hanya soal kepemilikan lahan atau izin, tetapi juga tentang siapa yang memiliki hak untuk mendefinisikan realitas.
Dalam kebijakan kehutanan, kata adalah bentuk kuasa yang paling subtil, ia bisa menghapus atau menghidupkan suara, tergantung siapa yang mengucapkannya dan dalam kerangka apa ia dipahami.
Dengan demikian, politik kehutanan adalah juga politik bahasa.
Dan politik bahasa, pada dasarnya, adalah politik representasi tentang siapa yang berhak menamai, menafsir, dan menentukan arah kebijakan atas nama “rakyat” dan “kelestarian.” Pendahuluan ini mengajak kita untuk berhenti sejenak di tengah kebisingan itu untuk bertanya “Apakah masyarakat hutan benar-benar berbicara, ataukah mereka sekadar disebut agar kebijakan tampak lebih manusiawi? Dan jika suara mereka benar-benar hilang di tengah keramaian wacana, siapakah yang diuntungkan oleh keheningan itu?”
Wajah Politik Representasi
Politik kehutanan di Indonesia tidak hanya hidup di balik meja perundingan atau naskah kebijakan, tetapi cara kita berbicara tentang hutan dan masyarakatnya. Bahasa kebijakan, slogan pembangunan, hingga laporan proyek, semuanya adalah *alat representasi* cermin yang memantulkan realitas, tetapi juga mengubah bentuknya. Sering kali yang tampak bukan wajah masyarakat hutan yang sesungguhnya, melainkan bayangan yang telah dikonstruksi oleh mereka yang memegang pena kekuasaan.
Negara, dengan seluruh aparatus hukum dan birokrasi yang diwariskan sejak kolonial, memonopoli posisi sebagai juru bicara utama atas nama hutan. Ia berbicara dengan legitimasi konstitusi, mengklaim mandat untuk “menguasai dan mengatur” demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun di balik legitimasi itu tersimpan logika dominasi bahwa negara tidak sekadar mengatur hutan, tetapi juga menentukan *makna* hutan itu sendiri, apa fungsi utamanya, siapa yang boleh mengaksesnya, dan dalam batas apa masyarakat dapat dianggap sah keberadannya.
Narasi “kepentingan nasional”, “keamanan kawasan”, dan “pembangunan berkelanjutan” menjadi mantra yang menjustifikasi kontrol. Melalui bahasa hukum dan kebijakan, negara menempatkan masyarakat bukan sebagai pemilik atau pengelola, tetapi sebagai penerima izin atau pihak yang diberdayakan. Dengan demikian, kekuasaan negara atas hutan tidak hanya bersifat material, melainkan juga simbolik yang mengatur bagaimana hutan dipahami dan bagaimana masyarakat dibayangkan.
Representasi menjadi wajah baru dari kekuasaan. Ia tidak bekerja dengan paksaan fisik, melainkan melalui *narasi dan citra*. Negara dan lembaga pembangunan menciptakan citra “masyarakat ideal”: kooperatif, adaptif, dan sesuai dengan tujuan proyek. Siapa pun yang melawan citra itu dianggap tidak rasional, keras kepala, atau bahkan anti-pembangunan. Representasi berfungsi sebagai *mekanisme penyaringan suara*, hanya suara yang sesuai dengan kerangka kuasa yang boleh terdengar.
Jika kita menelusuri lebih jauh, wajah politik representasi ini memiliki akar historis panjang. Sejak masa kolonial, hutan didefinisikan sebagai “domain negara”, dan masyarakat lokal ditempatkan sebagai penghuni liar yang harus ditertibkan. Pola ini berlanjut pasca-kemerdekaan bahwa meski rezim berubah, bahasa kekuasaan tetap sama. Hanya terminologinya yang berganti, dari “ketertiban” menjadi “keberlanjutan”, dari “penguasaan” menjadi “pengelolaan.” Tetapi dua-duanya, suara masyarakat tetap bergema dalam ruang yang ditentukan orang lain. Pertanyaannya adalah apakah partisipasi yang dirayakan selama ini benar-benar membuka ruang bagi masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri? Ataukah ia hanya memperhalus mekanisme lama, di mana kekuasaan berbicara atas nama rakyat agar tetap bisa memutuskan tanpa mereka?
Masyarakat yang Dibisukan
Tiap kebijakan kehutanan, masyarakat hutan selalu disebut sebagai “penerima manfaat utama”. Kalimat itu tampak luhur dan meyakinkan, seolah negara dan lembaga pembangunan bekerja untuk mereka. Namun, di balik kalimat yang indah itu tersembunyi kenyataan yang pahit bahwa *masyarakat hutan jarang benar-benar berbicara atas namanya sendiri*. Mereka hadir dalam teks, tetapi tidak dalam ruang pengambilan keputusan. Nama mereka muncul di laporan, tetapi tidak di forum yang menentukan arah kebijakan. Mereka dipotret dalam dokumentasi proyek, tetapi jarang diminta pandangan ketika desain program dirumuskan. Dengan kata lain, masyarakat hutan menjadi simbol kehadiran, bukan aktor yang sungguh hadir.
Kebisuan ini bukan karena mereka tidak memiliki suara, tetapi karena bahasa mereka tidak diakui oleh sistem kekuasaan yang dibangun atas dasar legalitas dan teknokrasi. Negara dan lembaga pembangunan menuntut bahasa yang formal, administratif, dan sesuai indikator. Sementara masyarakat berbicara dengan bahasa pengalaman, nilai, dan kehidupan sehari-hari. Dalam pertemuan dua dunia bahasa ini, yang sering terjadi bukan dialog, melainkan penyaringan suara bahwa hanya yang sesuai dengan tata bahasa kekuasaan yang dianggap layak masuk berita acara.
Padahal, di balik kebisuan itu, tersimpan pengetahuan yang tak ternilai. Setiap tindakan kecil memilih waktu menebang, menanam kembali pohon tertentu, menjaga mata air, atau menentukan wilayah larangan adat adalah bentuk tuturan ekologis yang lahir dari generasi panjang pengalaman hidup. Namun, kebijakan modern jarang menganggap itu sebagai “pengetahuan.” Yang disebut pengetahuan adalah peta spasial, laporan statistik, dan dokumen teknis. Akibatnya, pengetahuan lokal dibungkam secara epistemik, masyarakat bukan hanya kehilangan suara, tetapi juga kehilangan hak untuk dianggap tahu.
Jika negara terus memaksa masyarakat berbicara dalam bahasa yang bukan miliknya, maka yang terjadi bukanlah komunikasi, tetapi kolonialisasi makna. Dan ketika bahasa rakyat tidak lagi dianggap sah, maka seluruh sistem kebijakan kehilangan akar moralnya. Sebab, bagaimana mungkin kita berbicara tentang keadilan ekologis, bila mereka yang paling hidup dalam ekologi itu tidak pernah diminta bicara?
Masyarakat yang dibisukan adalah cermin dari kegagalan representasi itu sendiri. Mereka bukan tidak punya kata, tetapi kata-kata mereka tidak muat dalam format yang dirancang oleh kekuasaan. Mereka bukan tidak punya gagasan, tetapi gagasan mereka tidak punya “tempat” dalam kebijakan. Sesungguhnya ada seruan paling keras agar negara dan lembaga pembangunan berhenti berbicara untuk mereka, dan mulai belajar mendengarkan dari mereka.
Bahasa Kekuasaan dan Politik Pengetahuan
Kekuasaan yang paling kuat bukanlah yang tampak dalam senjata, pasal, atau kekuatan koersif, melainkan kekuasaan yang tersembunyi di balik bahasa, karena bahasa tidak hanya menggambarkan dunia, tetapi juga menciptakan dunia. Bahasa kebijakan telah lama menjadi medan pertempuran yang menentukan siapa yang berhak menamai, siapa yang didefinisikan, dan siapa yang didefinisikan _oleh_ pihak lain. Negara dan lembaga pembangunan mengatur dunia sosial dan ekologis ke dalam kategori-kategori yang bisa diukur seperti izin kelola, kawasan lindung, kemitraan, pemberdayaan, monitoring, output, outcome. Kata-kata itu tampak ilmiah dan netral, padahal setiap istilah menyembunyikan ideologi bahwa siapa yang memegang kontrol, siapa yang mengatur perilaku siapa, dan siapa yang memperoleh legitimasi moral dari istilah tersebut.
Ambil contoh kata “pemberdayaan masyarakat”. Ia terdengar penuh niat baik, tetapi menyimpan asumsi bahwa masyarakat pada dasarnya lemah dan perlu diberdayakan. Negara dan lembaga pembangunan menempatkan diri sebagai “pemberi daya,” dan masyarakat sebagai “penerima daya.” Relasi ini menciptakan asimetri epistemik, hanya satu pihak yang berhak mendefinisikan kebenaran, sementara pihak lain ditempatkan sebagai obyek perbaikan. Keheningan masyarakat dianggap tanda ketidaktahuan, padahal bisa jadi itu adalah cara mereka menjaga kearifan.
Foucault menyebut mekanisme seperti ini sebagai regime of truth atau rezim kebenaran. Artinya, hanya jenis pengetahuan tertentu yang diakui sah oleh institusi dianggap lebih valid daripada ingatan kolektif masyarakat tentang batas hutan, laporan proyek dianggap lebih kredibel daripada kesaksian adat tentang sejarah lahan. Maka, yang dimenangkan bukan hanya argumentasi, tetapi seluruh cara berpikir tentang hutan itu sendiri.
Maarten Hajer (1995) menyebut proses ini sebagai discourse coalition atau koalisi wacana yang menyatukan berbagai aktor di bawah narasi yang tampak progresif tetapi sebenarnya memelihara struktur kekuasaan lama.
Bahasa kekuasaan tidak bekerja dengan paksaan langsung, ia bekerja dengan persuasi epistemik. Ia menanamkan keyakinan bahwa hanya dengan mengikuti bahasa resmi seseorang bisa diakui sebagai bagian dari solusi. Itulah sebabnya banyak tokoh lokal yang terpaksa belajar “berbahasa proyek” agar dianggap kompeten oleh birokrasi. Mereka menyesuaikan tutur dan konsepnya dengan format proposal, meski harus menyingkirkan istilah-istilah adat yang sesungguhnya lebih bermakna. Maka lahirlah generasi baru “wakil masyarakat” yang piawai berbicara dalam bahasa kebijakan, namun perlahan tercerabut dari akar makna komunitasnya sendiri.
Tania Li (2007) menggunakan istilah rendering technical bahwa proses menjinakkan kompleksitas sosial menjadi masalah teknis yang dapat diatur dan diukur. “Kemiskinan,” “konflik,” dan “akses” diubah menjadi kategori yang bisa diintervensi lewat indikator, tanpa menyentuh akar strukturalnya yaitu ketimpangan kekuasaan. Proyek kehutanan sosial, program karbon, dan inisiatif konservasi sering kali menjadi contoh klasik: setiap masalah diterjemahkan ke dalam logika proyek, bukan logika kehidupan.
Namun, di balik semua itu, ada bahaya yang lebih halus yaitu *pemusnahan epistemik*. Pengetahuan lokal yang hidup dalam laku, bahasa, dan spiritualitas, secara perlahan dianggap tidak valid karena tidak bisa dibuktikan dengan metode ilmiah. Seperti kata Spivak dalam pertanyaan terkenalnya, “Can the Subaltern Speak?”, masyarakat lokal bisa berbicara, tetapi apakah dunia mendengar dengan telinga yang mampu memahami bahasa mereka?
Kita perlu menyadari bahwa di balik setiap istilah kebijakan tersimpan pilihan moral. Ketika negara menyebut “kemitraan kehutanan”, siapa yang sesungguhnya menjadi mitra, dan siapa yang ditentukan arah kemitraannya? Ketika lembaga donor menulis “partisipasi”, sejauh mana masyarakat berpartisipasi dalam merumuskan arti partisipasi itu sendiri? Bahasa seperti ini membangun dunia yang tertib, tetapi kerap tanpa keadilan. Maka, melawan ketimpangan kekuasaan berarti juga melawan hegemoni bahasa. Ini bukan sekadar perdebatan akademik, tetapi perjuangan untuk mengembalikan hak masyarakat menamai dan menafsir dunianya sendiri. Sebab, hanya dengan mengembalikan kedaulatan atas makna, kita bisa membebaskan kebijakan dari tirani kata-kata yang indah tetapi hampa.
Kita belajar bahwa hutan bukan sekadar ruang yang dipetakan, melainkan ruang yang diceritakan. Dan selama cerita tentang hutan hanya ditulis oleh mereka yang jauh dari pohon-pohon itu, maka yang tumbuh bukanlah kebijakan yang adil, melainkan bayangan kuasa yang terus memperbanyak diri lewat bahasa.
Membayangkan Politik Representasi yang Baru
Setelah sekian lama hutan dan masyarakatnya hidup dalam bayang-bayang bahasa kekuasaan, pertanyaan yang muncul kini bukan lagi sekadar “siapa yang berkuasa”, tetapi “bagaimana kita dapat mengubah cara kekuasaan berbicara”. Sebab, keadilan tidak mungkin lahir dari bahasa yang menyingkirkan dan partisipasi tidak akan bermakna jika hanya menjadi upacara simbolik untuk meneguhkan wacana lama. Untuk itu, kita perlu membayangkan politik representasi yang baru, politik yang tidak dimulai dari klaim “berbicara untuk rakyat”, tetapi dari kesediaan untuk “mendengarkan rakyat berbicara dengan bahasanya sendiri”.
Jurgen Habermas menyebut ini sebagai communicative action atau tindakan komunikasi yang sejati, di mana rasionalitas tidak diukur dari kepentingan teknis tetapi dari keterbukaan terhadap argumentasi dan pengakuan atas posisi setara. Hal ini berarti membuka kembali proses pengambilan keputusan dari bentuk monolog administratif menuju dialog deliberatif. Forum yang selama ini kaku dan birokratis perlu diubah menjadi ruang yang mampu menampung cerita, keyakinan, dan pengalaman masyarakat, bukan sekadar laporan kegiatan.
Tentu, membayangkan politik representasi yang baru bukan sekadar soal prosedur partisipasi. Ia menuntut transformasi epistemik, perubahan cara kita memahami pengetahuan dan kebenaran. Paulo Freire mengingatkan bahwa pembebasan tidak datang dari “mendidik rakyat,” tetapi dari “belajar bersama rakyat”. Masyarakat bukan obyek yang harus diberdayakan, melainkan subjek pengetahuan yang sudah memiliki daya, pengalaman, dan kebijaksanaan yang sah. Dengan begitu, pemberdayaan sejati bukanlah memberi suara kepada yang bisu, tetapi menghapus struktur yang membisukan.
Ruang deliberasi tidak hanya diadakan di hotel atau ruang rapat pemerintah, tetapi juga di bale desa, di hutan adat, di ladang yang sedang dibuka. Bahasa resmi tidak lagi menjadi satu-satunya alat komunikasi, bahasa simbolik, ritual, dan narasi kehidupan sehari-hari diakui sebagai bagian dari ekologi pengetahuan. Seperti dikatakan Boaventura de Sousa Santos, kita perlu membangun ecology of knowledges atau ekologi pengetahuan, di mana ilmu modern hidup berdampingan dengan kebijaksanaan lokal tanpa saling menyingkirkan.
Politik representasi yang baru juga memerlukan kerendahan hati epistemik. Artinya, para ahli, pejabat, dan pengambil kebijakan harus mengakui bahwa tidak ada satu cara pandang pun yang mampu memahami hutan secara utuh. Sebab hutan tidak hanya terdiri dari tegakan kayu dan karbon, tetapi juga dari ingatan, rasa takut, dan cinta bahwa hal-hal yang tidak bisa dihitung, tetapi justru membuat kehidupan di dalamnya bermakna. Kerendahan hati epistemik inilah yang membuka jalan bagi dialog sejati, dialog yang tidak dimulai dari niat untuk mengatur, tetapi dari niat untuk memahami.
Membayangkan politik representasi yang baru berarti membayangkan tata kelola yang benar-benar multi-vokal, di mana kebijakan menjadi hasil dari pertemuan berbagai suara, bukan keputusan tunggal dari satu sumber kebenaran. Di sini, kekuasaan tidak dihapus, tetapi distrukturkan ulang menjadi kekuasaan yang terbagi, negara menjadi fasilitator, masyarakat menjadi pengambil keputusan, dan pasar hanya boleh beroperasi dalam batas etika ekologis.
Arah ini mungkin tampak utopis, tetapi ia bukan utopia kosong. Embrio politik representasi baru telah tumbuh, dalam musyawarah adat yang menentukan batas hutan, dalam inisiatif masyarakat yang mengelola hutan dengan prinsip gotong royong, dalam komunitas perempuan yang menata ekonomi berbasis hasil hutan bukan kayu, dalam pemuda-pemudi yang membangun narasi digital tentang identitas ekologis mereka. Semua itu adalah bentuk *_representasi otentik_*, bukan yang diberikan dari luar tetapi yang tumbuh dari dalam.
Politik representasi yang baru tidak berangkat dari niat menggantikan sistem lama, tetapi dari kesadaran bahwa sistem lama telah kehilangan jiwa. Selama bahasa kebijakan hanya memantulkan suara kekuasaan, maka kebijakan akan terus kehilangan legitimasi moralnya. Tetapi ketika bahasa kebijakan mulai memantulkan keberagaman pengalaman dan pengetahuan rakyat, di situlah kekuasaan menemukan maknanya yang sejati sebagai alat untuk melindungi kehidupan, bukan mengaturnya dari jauh.
Maka, langkah pertama menuju politik representasi yang baru bukanlah membuat program baru, melainkan belajar mendengar dengan cara baru. Sebab mungkin, suara masyarakat hutan sebenarnya tidak pernah hilang hanya kita saja yang terlalu bising untuk mendengarnya.
Penutup: Dari Representasi Menuju Emansipasi
Setelah menelusuri sejarah panjang kekuasaan yang berbicara atas nama rakyat, kita akhirnya sampai pada kesadaran yang paling mendasar bahwa “masalah terbesar dalam tata kelola hutan bukan hanya siapa yang berkuasa, tetapi siapa yang berhak berbicara”. Selama ini, negara, lembaga donor, dan pasar berlomba mengklaim diri sebagai penjaga kepentingan masyarakat dan hutan. Mereka berbicara dengan niat baik, dengan bahasa yang terdengar ilmiah, modern, dan penuh moralitas. Tetapi di balik itu semua, suara masyarakat tetap teredam oleh lapisan-lapisan representasi yang menyingkirkan otonomi mereka untuk mendefinisikan diri.
Kita hidup dalam zaman di mana bahasa kepedulian dapat dengan mudah menutupi praktik pengendalian. Istilah seperti “pemberdayaan”, “partisipasi”, dan “keberlanjutan” bertebaran di setiap kebijakan, tetapi sering kali kehilangan makna substansialnya. Partisipasi berubah menjadi prosedur, pemberdayaan menjadi administrasi, keberlanjutan menjadi laporan. Kekuasaan tidak lagi tampak menindas secara terang-terangan, tetapi hadir dalam bentuk kasih sayang yang menundukkan, paternalistik, halus, dan terlegitimasi.
Oleh karena itu, politik representasi harus melampaui retorika. Ia harus bertransformasi menjadi politik emansipasi, yang tidak berhenti pada memberi tempat bagi suara masyarakat, tetapi mengembalikan hak mereka untuk menentukan makna dari kehidupan mereka sendiri. Emansipasi berarti masyarakat tidak lagi berbicara dengan bahasa yang dipinjam dari negara, melainkan dengan bahasa yang tumbuh dari tanah dan sejarah mereka sendiri.
Dalam kerangka emansipasi, hutan bukan lagi “objek pengelolaan,” tetapi ruang kehidupan bersama yang dijaga oleh etika saling percaya. Negara tidak lagi menjadi pengatur tunggal, tetapi mitra dalam memastikan keadilan dan keberlanjutan. Kebijakan tidak lagi disusun untuk masyarakat, tetapi bersama mereka. Emansipasi, dengan demikian, bukan sekadar kebebasan dari dominasi, tetapi kebebasan untuk memaknai diri dan dunianya secara mandiri.
Kita dapat belajar dari banyak komunitas di pelosok negeri,